Membumikan Resolusi Jihad Santri

PUTUSAN sejarah perjuangan para santri dalam mempertahankan negara dan mengusir penjajah yang sempat terlupakan dan sengaja dilupakan menggeliat muncul ke permukaan sejak presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional (HSN).
Keppres perayaan Hari Santri Nasional itu didasarkan pada perjuangan para santri se Jawa dan Madura dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dengan bekal semangat “Resolusi Jihad” yang difatwakan Hadratusy Syekh Hasyim Asy’ari, Rais ‘Am PBNU kala itu.
Keluarnya fatwa Resolusi Jihad itu merupakan peristiwa sejarah, dan bagi umat Islam Indonesia, para santri khususnya, resolusi itu sejatinya ditempatkan sebagai teks sejarah yang menginspirasi secara politik dan agama, tetapi tidak harus disakralisasi. Penegasan ini penting agar pernyataan melanjutkan perjuangan bersifat fi sabilillah yang terdapat di dalam Resolusi Jihad itu bisa dipahami sebagai pandangan Islam tentang bela negara dan pilihan bentuk negara yang tidak harus berbentuk negara Islam.
Negara apapun boleh dipilih dan dibela selama nilai-nilai Islam memberinya inspirasi, Islam dijamin di dalamnya, dan karena itu umat Islam secara individu wajib membela dan mempertahankannya. Begitu juga sejatinya kita menempatkan pengertian “santri” dalam pengertiannya yang luas, agar setiap orang Islam yang ada di Indonesia merasakan dan mendapatkan inspirasi dari semangat perjuangan bela negara para santri masa lalu itu.
Istilah santri dan jihad yang menjadi topik utama Hari Santri Nasional sejatinya mengalami perkembangan makna (konseptual), dan kedua istilah inilah yang hendak dideskripsi dalam tulisan ini.
Harapannya sederhana, yakni agar tidak hanya mereka yang belajar di pondok pesantren yang boleh merayakan peringatan hari santri nasional itu, tetapi juga setiap orang yang dicakup oleh makna santri itu sendiri. Begitu juga agar para santri itu tidak sekedar merayakan hari bersejarah itu secara serimonial belaka tetapi hampa makna, melainkan agar mendapatkan inspirasinya dari semangat jihad mereka di masa lalu untuk kemudian dijadikan pijakan melihat masa depan.
Istilah santri yang sebenarnya sudah lama muncul di Indonesia mengalami perkembangan makna sejalan dengan perkembangan kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia yang multikultur dan multireligius.
Pertama, istilah santri pada awalnya dikenal dalam tradisi non Islam, lalu diadopsi dan diterapkan di dalam sistem pendidikan tradisional Pondok Pesantren yang diasuh seorang Kyai dan bu Nyai, yang di dalamnya ada santri. Santri adalah seseorang yang belajar agama di Pondok Pesantren, baik mereka bermukim maupun tidak bermukim.
Di dalam pondok pesantren, terdapat masjid, kamar-kamar untuk hunian santri, dapur untuk tempat memasak, dan tentu saja terdapat pembelajaran kitab kuning, baik dalam bentuk sorogan maupun klasikal. Karena Pondok Pesantren mempunyai sistem dan pola kehidupan sendiri yang berbeda dan otonom dari sistem dan pola kehidupan masyarakat pada umumnya, Gus Dur menyebut pondok pesantren sebagai subkultur masyarakat.
Kedua, istilah santri dengan makna baru muncul dari antropolog Amerika Clifford Geert. Ketika melakukan penelitian etnografi di masyarakat Mojokuto Kediri Jawa Timur, Geert menemukan tiga tipologi masyarakat di sana, yakni santri, abangan dan priyai. Ketiga tipe itu menunjuk pada komunitas masyarakat yang berbeda, baik dilihat dari sisi kehidupan keberagamaannya maupun strata sosialnya.
Geert memasukkan istilah santri sebagai kategori keberagamaan yang diacukan kepada seorang muslim yang taat menjalankan ibadah kepada Allah. Siapa saja yang muslim dan menjalankan ibadah secara taat, dia bisa disebut santri. Tidak ada persyaratan harus belajar dan menetap di pondok pesantren untuk disebut santri sebagaimana tipe pertama.
Pengertian santri seperti ini mengeluarkan mereka yang muslim tetapi tidak taat beribadah kepada Allah, dan menyebutnya sebagai abangan. Abangan menunjuk pada mereka yang mungkin muslim tetapi tidak taat beribadah, atau mereka yang mengikuti agama Jawa yang singkritis.
Priyai sebenarnya sebagai kategori sosial, yakni sekelompok orang yang secara sosial berada pada posisi tertentu di masyarakat Mojokuto, tanpa dikaitkan dengan kehidupan keberagamaannya. Mereka bisa saja seorang muslim, bisa juga penganut agama Jawa.
Kedua tipe santri itu tidak hanya berbeda dari segi maknanya, tetapi juga dari segi teritori dan subyeknya. Teritori santri tipe pertama sebatas Pondok Pesantren, sedang teritori santri tipe kedua lebih luas meliputi kampung tertentu yang berada di suatu desa namanya Mojokuto di Kediri, yang kemudian digeneralisasi. Teritori kedua lebih luas dari yang pertama.
Tetapi jika dilihat dari sisi subyeknya (santrinya), tipe yang pertama lebih luas dari tipe yang kedua, karena yang pertama mencakup para santri yang berasal dari tempat yang berbeda-berbeda yang tersebar di Indonesia, baik dari sisi tempat maupun etnisnya. Sedang tipe yang kedua sebatas masyarakat tertentu yang berada di daerah Mojokuto.
Ketiga, belakangan muncul lagi istilah santri dengan mendapat tambahan kata “maha” di depannya sehingga menjadi “mahasantri”, yakni para mahasiswa yang belajar agama di Pondok Pesantren yang dikelola oleh Perguruan Tinggi, yang disebut ma’had al-Jami’ah. Penambahan istilah “maha” di depan kata “santri” menjadi pembeda dengan dua tipe santri sebelumnya, karena kata “maha” mengacu pada mahasiswa yang sedang belajar di Perguruan Tinggi.
Yang menjadi inti dari nama “mahasantri” adalah mahasiswanya, sedang istilah santri merupakan sifat yang dilabelkan kepada mahasiswa yang sambal belajar di ma’had al-jami’ah. Pengertian ini mengeluarkan para mahasiswa yang tidak belajar di ma’had al-Jami’ah, kendati mereka seorang muslim.
Akan tetapi, karena ketiga tipe santri itu tidak mengarah pada kontradiksi logis dan faktual, melainkan sebuah perkembangan dan perluasan makna dari istilah santri itu sendiri, maka mereka yang merasa sebagai orang Islam yang taat beribadah, baik mereka yang belajar di Pondok Pesantren tradisional dan modern maupun tidak; baik mahasiswa yang belajar di Pondok Kampus (ma’had al-Jami’ah) maupun tidak, bisa disebut sebagai santri. Atas dasar itu, mereka berhak merayakan Hari Santri Nasional, termasuk mahasiswa yang tidak belajar di Pondok Pesantren (ma’had al-Jami’ah),-kecuali mahasiswa non-muslim,- karena dalam pengertian Geert, mereka masuk kategori santri.
Di sisi lain, kita juga perlu memahami secara tepat konsep jihad yang menjadi subyek Resolusi Jihad yang menggerakkan perjuangan para santri melawan penjajah untuk membela negara Indonesia yang baru dideklarasikan, agar mereka tidak salah dalam memahami dan menggunakannya saat ini dan ke depan.
Apalagi, di dalam Resolusi Jihad itu terdapat istilah fi sabilillah, yang jika telinga kita mendengar istilah jihad fi sabilillah, pikiran kita biasanya mengarah pada doktrin teologis perang suci melawan orang-orang kafir, yang belakangan istilah kafir itu juga mengalami perkembangan makna sebagaimana istilah jihad.
Pikiran seperti itu muncul lantaran sebagian orang selalu menampilkan ayat-ayat perang dalam mendakwahkan Islam. Jika pun terdapat ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang kasih sayang, rahmatan li al-alamin, dan toleran terhadap penganut agama lain, mereka berkilah sudah dinasakh oleh ayat perang dengan menggunakan teori nasakh, suatu istilah yang kendati muncul di dalam al-Qur’an tetapi dipahami secara salah hanya demi menjustifikasi ideologi kaku dan kerasnya dalam menghadapi penganut agama lain.
Untuk menghindari kesalahpahaman itu, berikut ini saya deskripsikan konsep jihad dalam al-Qur’an serta Resolusi Jihad seperti apa yang dibutuhkan para santri ke depan.
Istilah Harb dalam pengertian qital (berperang) di dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak empat kali, sedang istilah jihad disebutkan sebanyak 32 kali. Sepuluh ayat turun di Makkah dengan pembagian: beberapa ayat turun pada fase Makkah pertengahan, seperti al-Ankabut: 6, 8, 69; Lukman:14-15; al-Fathir:42), dan sebagian ayat lagi turun pada fase Makkah akhir, seperti al-Haj:78; al-An’am:110; al-Nahl:110; dan al-Furqan: 52. Sisanya turun di Madinah.
Istilah jihad dalam al-Qur’an juga mengalami perkembangan makna sejalan dengan gerak dakwah nabi Muhammad di dua tepat suci itu. Ketika turun di Makkah, ayat-ayat jihad bermakna jihad diri “al-jihad al-nafsi” (Lukman:15; al-Ankabut:69), yakni sikap umat Islam agar bersabar (al-Ma’arij:5; al-Ashr:3) dalam menghadapi kezaliman orang-orang musyrik Makkah.
Jihad seperti ini disebut jihad besar (al-Furqan:52). Di Makkah juga diperintah untuk berjihad harta “al-jihad al-mal” (al-Hujrat:15) agar umat Islam yang mempunyai harta cukup untuk memberikan bantuan harta kepada orang-orang Islam yang hendak hijrah ke (Yatsrib) Madinah lantaran harta mereka ditinggal dan dirampas oleh orang-orang kafir Makkah. Jihad harta dinilai penting sehingga di dalam al-Qur’an, penyebutan jihad harta didahulukan daripada jihad diri (al-Taubah:41).
Konon, tidak ada istilah jihad yang bermakna perang selama di Makkah. Baru di Madinah lah, ayat-ayat jihad mengambil arti peperangan, karena di sana mulai muncul tekanan kepada umat Islam untuk berperang, sementara nabi Muhammad dan umat Islam diizinkan berperang oleh Allah. Akan tetapi, jihad dalam arti berperang tidak dalam posisi aktif menyerang, melainkan dalam posisi pasif, yakni membela diri dari serangan lawan.
Pada periode, Nabi Muhammad dan umat Islam berada dalam posisi “diizinkan” memerangi orang-orang zalim yang “mengusir” mereka dari rumahnya, yakni Makkah (al-Haj:39-40), dan juga karena umat Islam sendiri berada dalam posisi “diperangi” lebih dulu (al-Baqarah:190).
Peperangan pada fase ini masih disebabkan oleh rasa “permusuhan” mereka terhadap nabi Muhammad dan umat Islam, bukan persoalan agama. Baru nabi Muhammad dan umat Islam diperintah memerangi orang-orang musyrik dengan alasan keagamaan, misalnya karena mereka tidak percaya kepada Allah (al-Taubah:29), dan terutama orang-orang musyrik Makkah pada periode Fathu Makkah (al-Baqarah:190-194; al-Taubah:36). Karena Makkah itu suci, dan orang musyrik itu najis, maka orang yang najis tidak boleh bertempat di tempat yang suci.
Kategorisasi dan perkembangan makna jihad dalam al-Qur’an itu mempunyai nilai yang berbeda dalam Islam. Jihad dalam arti berperang oleh nabi Muhammad disebut jihad kecil (al-jihad al-Asghar), sedang jihad dalam arti mengelola jiwa agar sabar menghadapi cobaan dan siksaan yang menyakitkan (al-jihad al-nafsi), serta menyumbangkan harta (al-jihad al-mal) di jalan Allah disebut jihad besar (al-jihad al-akbar). Perbedaan nilai itu dinyatakan langsung oleh Nabi Muhammad begitu kembali dari perang Badar yang dahsyat itu, “kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar”.
Perbedaan kedua kategori jihad itu juga berkaitan dengan hukum dan tanggung jawab masing-masing individu. Jika jihad kecil dihukumi fardu kifayah, sehingga jika sudah ada sebagian umat Islam yang berjuang melawan orang-orang zalim, maka sebagian yang lainnya tidak diwajibkan ikut berperang, maka jihad besar dihukumi fardu ain, karena perlawanan menjaga diri agar sabar dan menjaga diri dari pengaruh syaitan merupakan tugas masing-masing individu.
Tugas ini tentu saja lebih berat, karena syaitan sebagai musuh yang tidak terlihat oleh mata senantiasa mengintai kelengahan kita sebagai manusia. Pada aspek ini, keimanan diperlukan oleh individu-individu.
Sementara dalam konteks yang lebih luas saat ini, santri memerlukan Relosusi Jihad baru. Karena saat ini, para santri sedang melawan ideologi-ideologi totaliter dari luar, baik dari Barat maupun Timur, Resolusi Jihad baru itu adalah Jihad Intelektual dengan basis epistemologi Islam moderat yang diasumsikan mampu menangkal gerakan ideologi-ideologi totaliter itu.
Kementerian Agama, sebagai ikon yang menjaga ke-Bhinnikaan dalam kehidupan beragama di Indonesia, adalah yang mencetuskan gagasan Islam moderat, kendati istilah itu sebenarnya sudah lama muncul dalan jagad pemikiran Islam. Kemenag juga sekaligus mempromosikan program “moderasi beragama” kepada masyarakat melalui pendirian Rumah Moderasi Beragama (RMB) di berbagai Lembaga Pendidikan keagamaan, Lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di bawahnya.
Akan tetapi, karena ideologi-ideologi totaliter baik yang sekular-liberal maupun yang radikal itu disebarkan melalui tegnologi digital yang tentu saja lebih dahsyat daripada penjajahan secara fisik oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun yang lalu, lantaran penjajahan model baru ini merasuk ke dalam diri setiap individu tanpa disadari, baik oleh individu sendiri maupun masyarakat, maka para santri juga harus “melek literasi digital”.
Maksudnya, selain dibekali kemampuan menggunakan tegnologi digital agar bisa menjadi konsumen sebagaimana masyarakat pada umumnya, para santri sejatinya juga menjadi agen yang mampu mengisi konten-konten media sosial, seperti Whatsap, Facebook, IG dan Youtube. Sebab, ada banyak informasi di dalam media sosial itu, tetapi tidak semua informasi itu bermanfaat.
Ada banyak informasi yang justru membahayakan keyakinan dan moralitas anak-anak bangsa, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konten-konten lainnya yang berbau ideologis. Di sinilah, para santri diharapkan mengisi media-media sosial itu dengan konten-konten yang bermoral dan terutama gagasan Islam moderat yang merahmati seluruh alam, terutama Indonesia.
Jika para santri tidak mempunyai kemampuan dalam bidang literasi digital, mereka akan tergilas oleh ideologi-ideologi totaliter itu. Apalagi, tegnologi digital yang sekarang menjangkiti dunia membuat kehidupan tidak lagi berjalan evolutif, dan revolusioner, melainkan desruptif, suatu perubahan super cepat yang berada di luar nalar kesadaran individu dan masyarakat. Siapa saja yang tidak mampu menguasai tegnologi digital dan tidak melek literasi digital, mereka akan didesrupsi oleh para ideolog-ideolog totaliter itu yang pada kenyataannya bergentayangan menguasai dunia maya.
Karena itu, mari kita rayakan Hari Santri Nasional kali ini, tidak hanya sebatas mengadakan upacara-upacara simbolik dengan menggunakan sarung dan kopiah hitam yang disimbolkan sebagai baju santri Nusantara, tetapi juga perlu diimbangi dengan memberdayakan mereka akan paham keislaman yang moderat dan mendorong mereka agar mengisi konten-konten media sosial dengan paham Islam moderat itu.
Dunia santri sekarang bukan dunia santri masa lalu, tantangan yang dihadapi santri sekarang tentu saja berbeda dengan tantangan yang dihadapi santri masa lalu. Begitu juga sejatinya, Resolusi Jihad yang diperlukan santri sekarang adalah Resolusi Jihad Intelektual yang mampu mengimbangi para penjajah baru yang berupa ideologi-ideologi totaliter itu yang kini bergerak melalui dunia maya.
Selamat merayakan Hari Santri Nasional
Penulis Aksin Wijaya, Dosen Fakultas Usuluddin IAIN Ponorogo dan Pengasuh Pesantren Literas Baitul Hikmah Ponorogo












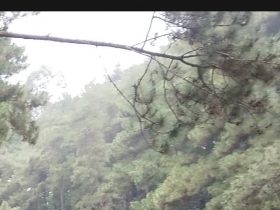

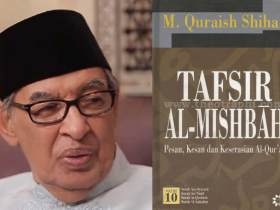
Leave a Reply